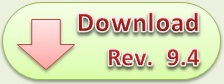AKSARA SUNDA KAGANGA
Aksara sepanjang sejarah perkembangannya merupakan lambang kemajuan adab
dan media untuk memacu perkembangan peradaban itu sendiri. Seperti kita ketahui, di
mana-mana, di dunia ini tatkala belum mengenal aksara, tingkat peradaban manusia
tergolong masih sangat rendah dan sangat sederhana. Kehidupan manusia cenderung
sangat tergantung kepada apa yang sudah disediakan oleh alam. Namun, setelah manusia
mengenal dan mempergunakan aksara, tingkat peradaban manusia makin tinggi dan
makin lama perubahan tingkat peradaban manusia itu semakin berlangsung cepat,
sehingga kehidupan manusia menjadi lebih kompleks.
Aksara, di sisi lain dipandang sebagai batas masa kehidupan manusia antara
zaman prasejarah (masa sebelum mengenal aksara) dengan zaman sejarah (masa sesudah
manusia mengenal dan mempergunakan aksara). Meskipun zaman prasejarah
berlangsung jauh lebih lama daripada zaman sejarah, namun pengetahuan tentang
kehidupan manusia prasejarah jauh lebih sedikit daripada pengetahuan kehidupan
manusia sejarah. Perbedaan kuantitas dan kualitas pengetahuan tersebut terutama
dimungkinkan oleh fungsi dan peranan aksara.
Masyarakat yang menghuni Tanah Sunda, misalnya sekitar 1500 tahun yang
silam, hanya menghasilkan tujuh buah prasasti (tulisan pada batu) yang panjang
keseluruhannya tidak lebih dari 100 kata dengan menggunakan jenis aksara dan bahasa
pinjaman dari India (Aksara Pallawa dan Bahasa Sansekerta). Sekitar 1000 tahun
kemudian mereka menulis tidak hanya pada batu, melainkan juga pada daun (lontar,
nipah) dan dengan menggunakan jenis aksara dan bahasa yang diciptakan sendiri (aksara
dan bahasa Sunda) serta panjang seluruh hasil tulisannya lebih dari puluhan ribu kata dan
isi tulisannya mengenai aneka macam aspek kebudayaan mereka. Sekitar 500 tahun
selanjutnya (tahun 2000) hasil karya tulis mereka tak terhitung lagi kuantitasnya, karena
terlalu banyaknya. Medianya pun sudah banyak sekali, seperti buku, majalah, surat kabar,
brosur, akte, arsip, kwitansi, surat. Contoh data-data di atas memperlihatkan betapa
makin maju dan berkembangnya kehidupan manusia serta makin lama makin cepatnya
kemajuan dan perkembangan itu. Semua itu terjadi antara lain berkat keberadaan, fungsi,
dan peran aksara. (Ekadjati, dalam Darsa, 2003: xiii).
Gambaran di atas memperlihatkan alasan mengapa aksara Sunda Kaganga perlu
dan harus dihidupkan lagi saat ini. Aksara Sunda yang diciptakan dan hasil kreasi orang
Sunda untuk mengabadikan pengetahuan dan pengalaman mereka di dalam bahasa Sunda
itu merupakan monumen penting yang menandakan tingginya tingkat peradaban yang
pernah dicapai oleh masyarakat Sunda pada masa silam. Suatu hal yang menjadi
kebanggaan kita sebagai ahli warisnya. Karena itu kita perlu mengenal warisan tersebut
serta memahami makna keberadaan dan peranannya. Mereka telah menyumbangkan
karya cipta mereka bagi kemajuan dan perkembangan peradaban. Untuk itulah tulisan ini
disusun, agar hasil kreativitas dan warisan orang Sunda pada masa silam itu dapat
dikenalkan kembali kepada generasi muda Sunda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya
khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini di sebagian masyarakat Sunda masih
ada anggapan bahwa model tulisan tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat
Sunda sama dengan model tulisan yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa, yang
lebih populer dengan sebutan Cacarakan atau Hanacaraka. Namun, sesungguhnya
semenjak tahun 1867, Holle sudah mulai merintis penggarapan naskah-naskah lontar
yang diperoleh dari wilayah Sunda. Sejak saat itu, Holle menyebutkan bahwa dalam
lontar-lontar tersebut berisi teks yang ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda Buhun.
Jejak Holle kemudian diikuti, antara lain oleh Pleyte (1911, 1914), Poerbatjaraka (1919-
1921), Dam (1957), Noorduyn (1962, 1965, 1982), Atja (1968, 1970). Atja dan
Danasasmita (1981 abc). Danasasmita, Ayatrohaedi, Wartini & Darsa (1987), Darsa &
Ekadjati (1995), Noorduyn & Teeuw (2000).
Naskah-naskah Sunda Buhun yang berbahan lontar ataupun nipah sampai saat ini,
yang telah berhasil digarap dan umumnya berasal dari abad XV-XVI Masehi di
antaranya: Carita Parahiangan, Sanghyang Siksa Kandang Karesian, Amanat
Galunggung, Kawih Paningkes, Jatiniskala, Carita Ratu Pakuan, Fragmen Carita
Parahiyangan, Sanghyang Hayu, Serat Dewa Buda, Serat Catur Bumi, Sang Hyang Raga
Dewata, Kisah Purnawijaya, Kisah Keturunan Rama dan Rahwana atau Pantun
Ramayana, Kisah Perjalanan Bujangga Manik, Sewaka Darma, Kisah Sri Ajnyana,
Darmajati, Jatiraga, Prabu Siliwangi, dan Mantra Aji Saka. Di samping itu, ada pula
teks-teks yang tertuang dalam bahasa yang lebih permanen berupa batu dan lempengan
logam, antara lain, prasasti-prasasti di Astana Gede dan Piagam Kebantenan. Teks-terks
tersebut secara jelas ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda Kuno.
Kenyataan seperti terungkap tadi, membuktikan bahwa masyarakat Sunda telah
mengenal tradisi tulis sejak lama, bahkan mereka telah mampu menciptakan sebuah
model aksara sendiri yang dikenal dengan aksara Sunda Kuno/Buhun. Naskah paling
muda yang menggunakan aksara Sunda Buhun berjudul Waruga Guru yang ditulis di
atas kertas ber-watermark. Rupa-rupanya mulai pertengahan abad XVIII Masehi aksara
Sunda Buhun mulai tenggelam karena secara kultural terdesak dengan adanya aksara
Cacarakan yang pembakuannya pertama kalinya dilakukan oleh Grashuis melalui
karangannya Handleiding voor Aanleren van het Soendaneesch Letterschrifjt ‘Buku
Petunjuk untuk belajar aksara Sunda’ yang terbit pada tahun 1860. Model aksara
Cacarakan tersebut tiada lain adalah hasil modifikasi dari aksara Carakan Jawa yang
telah dibakukan sebelumnya oleh Roorda pada tahun 1835.
Dalam tulisan ini, Aksara Sunda Kaganga tersebut berupaya dikenalkan kembali
untuk memperlihatkan kembali salah satu unsur budaya Sunda hasil kreativitas generasi
Sunda terdahulu. Upaya ini ternyata mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat
yang terbukti dengan dikeluarkannya Perda no. 6 tahun 1996 dan kemudian diikuti
dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah TK. I Jawa Barat No. 434/SK.614-
Dis.PK/99. Adanya Perda dan SK Gubernur ini pun dilatarbelakangi oleh Keputusan
Presiden No. 082/B/1991 tanggal 24 Juli 1991. Perda nomor 6 tahun 1996 tersebut kini
sudah disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini menjadi “Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2003” Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan
Aksara Daerah.
Adapun mengenai Aksara Sunda yang dikenalkan dalam tulisan ini tidak persis
sama dengan aksara Sunda Kuno atau Buhun, tetapi telah dilakukan sedikit modifikasi
oleh para pakar dari kalangan perguruan tinggi (Unpad, UI, UPI), khususnya mereka
yang berkecimpung dalam bidang Filologi. Upaya modifikasi ini dilakukan demi
kepraktisan pemakaian aksara Sunda guna merekam bahasa Sunda yang terus mengalami
proses perkembangan, dengan tidak lepas dari tipologi dasar aksara Sunda Buhun dari
abad XV-XVI Masehi.
untuk Lebih Jelas Silahkan download disini
Bentuk Aksara Sunda Kaganga
dan media untuk memacu perkembangan peradaban itu sendiri. Seperti kita ketahui, di
mana-mana, di dunia ini tatkala belum mengenal aksara, tingkat peradaban manusia
tergolong masih sangat rendah dan sangat sederhana. Kehidupan manusia cenderung
sangat tergantung kepada apa yang sudah disediakan oleh alam. Namun, setelah manusia
mengenal dan mempergunakan aksara, tingkat peradaban manusia makin tinggi dan
makin lama perubahan tingkat peradaban manusia itu semakin berlangsung cepat,
sehingga kehidupan manusia menjadi lebih kompleks.
Aksara, di sisi lain dipandang sebagai batas masa kehidupan manusia antara
zaman prasejarah (masa sebelum mengenal aksara) dengan zaman sejarah (masa sesudah
manusia mengenal dan mempergunakan aksara). Meskipun zaman prasejarah
berlangsung jauh lebih lama daripada zaman sejarah, namun pengetahuan tentang
kehidupan manusia prasejarah jauh lebih sedikit daripada pengetahuan kehidupan
manusia sejarah. Perbedaan kuantitas dan kualitas pengetahuan tersebut terutama
dimungkinkan oleh fungsi dan peranan aksara.
Masyarakat yang menghuni Tanah Sunda, misalnya sekitar 1500 tahun yang
silam, hanya menghasilkan tujuh buah prasasti (tulisan pada batu) yang panjang
keseluruhannya tidak lebih dari 100 kata dengan menggunakan jenis aksara dan bahasa
pinjaman dari India (Aksara Pallawa dan Bahasa Sansekerta). Sekitar 1000 tahun
kemudian mereka menulis tidak hanya pada batu, melainkan juga pada daun (lontar,
nipah) dan dengan menggunakan jenis aksara dan bahasa yang diciptakan sendiri (aksara
dan bahasa Sunda) serta panjang seluruh hasil tulisannya lebih dari puluhan ribu kata dan
isi tulisannya mengenai aneka macam aspek kebudayaan mereka. Sekitar 500 tahun
selanjutnya (tahun 2000) hasil karya tulis mereka tak terhitung lagi kuantitasnya, karena
terlalu banyaknya. Medianya pun sudah banyak sekali, seperti buku, majalah, surat kabar,
brosur, akte, arsip, kwitansi, surat. Contoh data-data di atas memperlihatkan betapa
makin maju dan berkembangnya kehidupan manusia serta makin lama makin cepatnya
kemajuan dan perkembangan itu. Semua itu terjadi antara lain berkat keberadaan, fungsi,
dan peran aksara. (Ekadjati, dalam Darsa, 2003: xiii).
Gambaran di atas memperlihatkan alasan mengapa aksara Sunda Kaganga perlu
dan harus dihidupkan lagi saat ini. Aksara Sunda yang diciptakan dan hasil kreasi orang
Sunda untuk mengabadikan pengetahuan dan pengalaman mereka di dalam bahasa Sunda
itu merupakan monumen penting yang menandakan tingginya tingkat peradaban yang
pernah dicapai oleh masyarakat Sunda pada masa silam. Suatu hal yang menjadi
kebanggaan kita sebagai ahli warisnya. Karena itu kita perlu mengenal warisan tersebut
serta memahami makna keberadaan dan peranannya. Mereka telah menyumbangkan
karya cipta mereka bagi kemajuan dan perkembangan peradaban. Untuk itulah tulisan ini
disusun, agar hasil kreativitas dan warisan orang Sunda pada masa silam itu dapat
dikenalkan kembali kepada generasi muda Sunda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya
khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini di sebagian masyarakat Sunda masih
ada anggapan bahwa model tulisan tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat
Sunda sama dengan model tulisan yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa, yang
lebih populer dengan sebutan Cacarakan atau Hanacaraka. Namun, sesungguhnya
semenjak tahun 1867, Holle sudah mulai merintis penggarapan naskah-naskah lontar
yang diperoleh dari wilayah Sunda. Sejak saat itu, Holle menyebutkan bahwa dalam
lontar-lontar tersebut berisi teks yang ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda Buhun.
Jejak Holle kemudian diikuti, antara lain oleh Pleyte (1911, 1914), Poerbatjaraka (1919-
1921), Dam (1957), Noorduyn (1962, 1965, 1982), Atja (1968, 1970). Atja dan
Danasasmita (1981 abc). Danasasmita, Ayatrohaedi, Wartini & Darsa (1987), Darsa &
Ekadjati (1995), Noorduyn & Teeuw (2000).
Naskah-naskah Sunda Buhun yang berbahan lontar ataupun nipah sampai saat ini,
yang telah berhasil digarap dan umumnya berasal dari abad XV-XVI Masehi di
antaranya: Carita Parahiangan, Sanghyang Siksa Kandang Karesian, Amanat
Galunggung, Kawih Paningkes, Jatiniskala, Carita Ratu Pakuan, Fragmen Carita
Parahiyangan, Sanghyang Hayu, Serat Dewa Buda, Serat Catur Bumi, Sang Hyang Raga
Dewata, Kisah Purnawijaya, Kisah Keturunan Rama dan Rahwana atau Pantun
Ramayana, Kisah Perjalanan Bujangga Manik, Sewaka Darma, Kisah Sri Ajnyana,
Darmajati, Jatiraga, Prabu Siliwangi, dan Mantra Aji Saka. Di samping itu, ada pula
teks-teks yang tertuang dalam bahasa yang lebih permanen berupa batu dan lempengan
logam, antara lain, prasasti-prasasti di Astana Gede dan Piagam Kebantenan. Teks-terks
tersebut secara jelas ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda Kuno.
Kenyataan seperti terungkap tadi, membuktikan bahwa masyarakat Sunda telah
mengenal tradisi tulis sejak lama, bahkan mereka telah mampu menciptakan sebuah
model aksara sendiri yang dikenal dengan aksara Sunda Kuno/Buhun. Naskah paling
muda yang menggunakan aksara Sunda Buhun berjudul Waruga Guru yang ditulis di
atas kertas ber-watermark. Rupa-rupanya mulai pertengahan abad XVIII Masehi aksara
Sunda Buhun mulai tenggelam karena secara kultural terdesak dengan adanya aksara
Cacarakan yang pembakuannya pertama kalinya dilakukan oleh Grashuis melalui
karangannya Handleiding voor Aanleren van het Soendaneesch Letterschrifjt ‘Buku
Petunjuk untuk belajar aksara Sunda’ yang terbit pada tahun 1860. Model aksara
Cacarakan tersebut tiada lain adalah hasil modifikasi dari aksara Carakan Jawa yang
telah dibakukan sebelumnya oleh Roorda pada tahun 1835.
Dalam tulisan ini, Aksara Sunda Kaganga tersebut berupaya dikenalkan kembali
untuk memperlihatkan kembali salah satu unsur budaya Sunda hasil kreativitas generasi
Sunda terdahulu. Upaya ini ternyata mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat
yang terbukti dengan dikeluarkannya Perda no. 6 tahun 1996 dan kemudian diikuti
dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah TK. I Jawa Barat No. 434/SK.614-
Dis.PK/99. Adanya Perda dan SK Gubernur ini pun dilatarbelakangi oleh Keputusan
Presiden No. 082/B/1991 tanggal 24 Juli 1991. Perda nomor 6 tahun 1996 tersebut kini
sudah disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini menjadi “Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2003” Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan
Aksara Daerah.
Adapun mengenai Aksara Sunda yang dikenalkan dalam tulisan ini tidak persis
sama dengan aksara Sunda Kuno atau Buhun, tetapi telah dilakukan sedikit modifikasi
oleh para pakar dari kalangan perguruan tinggi (Unpad, UI, UPI), khususnya mereka
yang berkecimpung dalam bidang Filologi. Upaya modifikasi ini dilakukan demi
kepraktisan pemakaian aksara Sunda guna merekam bahasa Sunda yang terus mengalami
proses perkembangan, dengan tidak lepas dari tipologi dasar aksara Sunda Buhun dari
abad XV-XVI Masehi.
untuk Lebih Jelas Silahkan download disini
Bentuk Aksara Sunda Kaganga